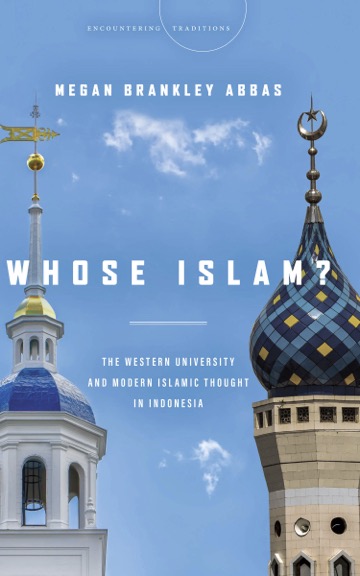 |
Judul: Whose Islam? The Western University and Modern Islamic Thought in Indonesia
Penulis: Megan Brankley Abbas
Penerbit: Stanford University Press, 2021
ISBN 9781503627932 (paper back)
Pendahuluan
Siapa yang memiliki otoritas untuk memahami suatu tradisi agama? Seperti apa metode yang sesuai untuk memahami tradisi tersebut? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan penting dan kerap kontroversial, yang menjadi bahan diskusi panjang bagi berbagai komunitas agama dan para pengkajinya, termasuk Islam. Dua pertanyaan tersebut juga menghantui para intelektual muslim di Indonesia dari berbagai generasi. Tidak hanya itu, berbagai jawaban yang diambil atas pertanyaan tersebut juga turut memengaruhi bentangan sosial-politik Tanah Air.
Problematika ini diangkat dan dibahas sejarawan Megan Brankley Abbas dalam buku perdananya, Whose Islam? The Western University and Modern Islamic Thought in Indonesia, yang disadur dari disertasi doktoralnya. Buku yang disajikan secara cukup padat ini mengangkat satu fenomena penting, yaitu peran sistem pendidikan Barat, terutama perguruan tinggi, dalam membentuk pemikiran Islam modern di Indonesia dan respons komunitas muslim, terutama para cendekiawannya, terhadap model produksi pengetahuan tersebut.
Abbas membuka bab pendahuluan dengan mengutip sejumlah bukti anekdotal dan fakta tentang posisi penting sistem universitas modern dan kampus-kampus Barat dalam proses produksi pengetahuan dan pembentukan otoritas keagamaan (Islam) di Indonesia. Fenomena itu tentu tidak saja tidak hadir dalam ruang hampa. Kondisi intelektual dan sosial yang melatarbelakangi kemunculan model produksi “hibrida” tersebut adalah kolonialisme Eropa atas bangsa-bangsa muslim yang kemudian melahirkan suatu krisis epistemik bertajuk dualisme intelektual (intellectual dualism, hal. 4). Bangunan pengetahuan Islam dan Barat dengan segala teks kanonikal, perangkat metodologis, model beroperasi, dan asumsi metafisisnya merupakan dua tradisi yang terpisah satu sama lain. Di dalam kondisi penjajahan, dualisme intelektual tentu meminggirkan basis pengetahuan Islam tradisional dan para pengikutnya, karena administrasi masyarakat kolonial menggunakan berbagai capaian dan kemajuan dalam pengetahuan modern “Barat” tersebut.
Menanggapi kondisi “keterbelakangan” tersebut, sejumlah pemikir dan intelektual muslim merumuskan satu rumusan intelektual baru, yaitu fusionisme. Abbas mendefinisikan fusionisme sebagai penolakan terhadap konsepsi dualisme pengetahuan Islam/Barat sebagai pembelahan yang artifisial dan mendorong konsepsi kebenaran yang lebih terpadu dan universal (hal. 7). Para pemikir fusionis fasih dalam leksikon serta bahasa pengetahuan Islam dan Barat. Mereka berupaya mengembangkan sintesis dari kedua tradisi tersebut. Fusionisme dekat dengan modernisme Islam yang menganggap bahwa Islam merupakan agama yang rasional dan progresif, yang mengedepankan ijtihad atau penafsiran kreatif berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah alih-alih taklid buta alias fanatisme terhadap satu tradisi atau ulama tertentu. Yang membedakan antara rumusan modernis dengan fusionis adalah penerimaan kelompok fusionis terhadap bentuk dan standar pengetahuan akademik modern sebagaimana dikembangkan di kampus-kampus Barat, satu hal yang tidak selalu bisa diterima oleh kalangan modernis.
Di dalam konteks pasca-kolonialisme dan Perang Dingin, kelompok fusionis menempati posisi yang tidak mudah. Beberapa dari mereka tertarik dan berpartisipasi dalam proses modernisasi developmentalis-otoritarian di negara-negara Selatan, termasuk Indonesia. Visi pembangunan masyarakat perspektif fusionis yang memiliki sejumlah keselarasan dengan model pembangunan otoritarian serta kompetensi intelektual dan administratif para tokohnya memfasilitasi kenaikan kaum fusionis dan pengaruh mereka dalam membangun komunitas epistemik dan institusi pendidikan tinggi. Akan tetapi, kedekatan kelompok fusionis dengan penguasa otoritarian dan upaya gigih mereka untuk melembagakan ide-ide fusionis mendapat tantangan dan kritik keras dari kelompok modernis non-fusionis dan para Islamis.
Abbas kemudian mengulas sejarah fusionisme Islam di Indonesia dari masa ke masa. Dia mengawali dengan membahas sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia di bab pertama. Diskriminasi dan marginalisasi di bawah kolonialisme Belanda mendorong perlawanan berbagai kelompok Islam terhadap dualisme intelektual. Koalisi “antidualis” ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok muslim modernis berpendidikan Timur Tengah seperti Muhammadiyah dan Kaum Muda, kelompok muslim berpendidikan Belanda seperti Jong Islamieten Bond (JIB), dan kelompok muslim tradisionalis yang berorientasi modern, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Pergolakan politik nasional di tengah-tengah penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tidak menyurutkan niat gerakan-gerakan Islam itu untuk membangun perguruan tinggi Islam. Ikhtiar itu akhirnya berbuah pada Maret 1948 dengan didirikannya Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Pada akhir 1949, upaya tersebut berlanjut ketika pemerintah republikan yang baru menasionalisasi fakultas agama UII dan mengubahnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang menjadi cikal bakal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) di kemudian hari.
Dua cendekiawan muslim yang berperan penting dalam membangun fondasi perguruan tinggi Islam di Indonesia ialah Mahmud Yunus dan Mohammad Natsir. Terinspirasi oleh pendidikannya di Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum di Kairo, Mahmud Yunus membawa semangat reformisme Islam ke dalam eksperimen kampus Islam di Indonesia. Yunus mendorong pendidikan Islam yang komprehensif dan modern, tetapi tidak melupakan aspek spiritual. Dia mewujudkan ide tersebut dengan mendesain kurikulum perkuliahan yang mengintegrasikan pendidikan bahasa Arab, kajian agama Islam, dan ilmu-ilmu umum seperti pengantar filsafat Barat, bahasa Inggris, dan kajian pendidikan di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Natsir, di sisi lain, aktif merumuskan dan memperjuangkan konsepsi Islam sebagai peradaban dan ideologi modern yang mampu menjawab tantangan zaman dan ancaman kolonialisme. Salah satu strategi intelektual dan retoris yang dipakai Natsir adalah menggunakan karya-karya sejumlah Orientalis terkemuka, seperti Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, Alfred Guillaume, dan Henri Pirenne untuk menunjukkan karakter komprehensif, rasional, dan progresif dari Islam. Menurut Abbas, Natsir memakai strategi itu untuk memperkuat klaimnya tentang kekuatan Islam. Meski visi kedua cendekiawan itu antidualis, kedua-duanya secara tidak langsung menerima suatu asumsi dualis bahwa ada perbedaan epistemik antara tradisi keilmuan Islam dan Barat/modern yang perlu dijembatani oleh institusi pendidikan tinggi Islam.
Menariknya, Abbas tidak hanya membahas tentang evolusi ide dan proses pembangunan kampus Islam oleh para muslim antidualis itu. Dia juga membahas tentang pergolakan politik yang memengaruhi eksperimen perguruan tinggi Islam pasca-penggabungan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN, terutama ketegangan antara Masyumi dan NU di masa Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno dan tantangan yang dihadapi oleh IAIN, seperti kurangnya jumlah tenaga dosen yang kompeten dalam tradisi Islam klasik dan juga ilmu-ilmu sosial modern.
***
Dalam Bab 2, Abbas membahas mengenai peran Universitas McGill sebagai “bidan” dari reformasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Wilfred Cantwell Smith, pendiri Institute of Islamic Studies (IIS) di McGill, berperan penting dalam merekrut sejumlah intelektual muslim Indonesia untuk melanjutkan studi pascasarjana di kampus tersebut. Rekrutmen generasi awal McGill menjadi fondasi untuk rekrutmen pada generasi-generasi selanjutnya. Abbas mencatat sampai tahun 2000-an, setidaknya 200 sarjana Indonesia telah menempuh studi master dan doktoral di McGill dan sekitar 1.400 staf dan pengajar IAIN telah mengikuti program kursus singkat tentang metode penelitian dan pengajaran di kampus yang sama (hal. 53).
Interaksi intelektual—dan bahkan politiko-etis—dari akademisi McGill dan cendekiawan muslim Indonesia yang bermula di tahun 1950-an itu menjadi landasan bagi konsolidasi visi fusionisme Islam ala Indonesia. Interaksi demikian menjadi titik kritis (critical juncture) dalam evolusi pemikiran Islam modern di Indonesia, yang bergerak dari visi antidualis ke visi fusionis yang lebih kaffah. Wilfred Cantwell Smith dari pihak McGill adalah promotor fusionisme yang gigih dari sisi “Barat.” Smith menggugat model “objektivitas” versi Orientalisme masa lalu yang terlampau skeptis dengan segala bentuk narasi tradisional Islam. Sebaliknya, Smith mencoba memahami Islam dan masyarakat muslim dari perspektif dan pengalaman “orang dalam.” Untuk mencapai pemahaman tersebut, Smith membangun IIS dan mengundang sarjana Barat dan muslim untuk berinteraksi secara intens dalam kerangka kajian ilmiah dan juga pemahaman antar-kebudayaan.
Walaupun demikian, interaksi antara pengkaji Islam modern dan sarjana muslim itu tidak selalu berjalan mulus. Impian Smith kadang terbentur oleh perlawanan terhadap fusionisme dari sejumlah sarjana muslim di IIS. Ismail Al-Faruqi, filsuf terkemuka muslim Amerika keturunan Palestina, terkenal dengan kritiknya yang keras terhadap imperialisme, berbagai bias Barat/Orientalis, dan kecenderungan positivis/saintisme dari kajian Islam modern (hal. 72-74). Dari Indonesia, kita mengenal Mohammad Rasjidi, intelektual cum politisi Masyumi lulusan Mesir dan Sorbonne. Seperti Al-Faruqi, Rasjidi pun resisten terhadap fusionisme kajian Islam ala Smith. Rasjidi menggunakan “kritik internal” filsafat Barat terhadap Marxisme, analisis Freudian, dan positivisme untuk menghadang pemikiran sekuler di Indonesia dan membela apologetika para sarjana muslim atas kebenaran teologis Islam sebagai sebuah pencapaian ilmiah (hal. 69-71).
Di sisi lain, ada sejumlah cendekiawan muslim yang dengan antusias merengkuh fusionisme, seperti Fazlur Rahman, Mukti Ali, dan Harun Nasution. Posisi mereka bisa dikatakan bergerak lebih jauh dari posisi koalisi antidualis gerakan Islam di Indonesia di masa pergerakan nasional dan awal kemerdekaan. Fazlur Rahman di kemudian hari menjadi mentor para cendekiawan muslim Indonesia di Universitas Chicago, sedangkan Mukti Ali dan Harun Nasution menjadi pejuang fusionisme terkemuka dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Setelah meraih gelar doktor dari McGill, Ali pulang ke Indonesia, menjadi profesor dan pelopor kajian perbandingan agama di IAIN, dan Menteri Agama (1971-1978). Harun Nasution adalah rekan seperjuangan Mukti Ali. Masa studinya di McGill merupakan periode transformatif – Nasution menjadi penganut teologi Mu’tazilah yang rasionalis, suatu komitmen keimanan dan intelektual yang juga menjadi topik disertasi doktoralnya.
Antusiasme Mukti Ali dan Harun Nasution tidak berhenti di ranah kajian akademik semata. Sebagai pembawa utama gagasan-gagasan fusionis, mereka juga melembagakan pendekatan kajian Islam yang mengintegrasikan sensibilitas historis-kritis dalam melihat perkembangan doktrin, konsep, sejarah, dan masyarakat Islam.
Bagaimana duet Mukti Ali-Harun Nasution menerjemahkan fusionisme di dalam konteks IAIN? Inilah yang menjadi fokus Abbas di bab ketiga. Dengan bantuan rekan cendekiawan muslim sesama lulusan McGill, Kafrawi Ridwan, dan juga dukungan dari pemerintah Orde Baru, Ali dan Nasution mendorong transformasi kurikulum di IAIN dan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kementerian Agama (Kemenag) melalui sejumlah langkah. Ideologisasi Islam, suatu konsepsi yang dekat dengan cita-cita Masyumi, ditentang Ali dan para kadernya sebagai suatu bentuk taklid. Alternatifnya adalah Islam yang “rasional,” “non-ideologis,” dan berorientasi program alias “pembangunan.” Untuk mendorong gagasan itu, Ali dan koleganya di Kemenag menerapkan—dan bukan hanya mengajarkan secara terpisah—metode ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam kajian agama di IAIN dan Kemenag serta menyediakan pendanaan dan beasiswa untuk pelatihan dan studi pascasarjana bagi staf pengajar dan peneliti di dua institusi tersebut. Di IAIN Jakarta, Harun Nasution, yang menjabat rektor selama satu dekade (1973-1984), juga mendorong agenda fusionis Ali secara masif dan komprehensif. Selain reformasi kurikulum dan agenda riset, Nasution juga menyempatkan diri menulis buku teks berorientasi fusionis bagi mahasiswa IAIN: Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.
Tentu saja, transformasi fusionis itu mendapat tantangan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang merupakan reinkarnasi Masyumi dan secara tegas memisahkan diri dari modernisme Islam dan memeluk Islamisme. Ironisnya, meski mengakui pentingnya ijtihad, Mohamad Rasjidi tetap percaya bahwa kebenaran dan validitas Islam serta segenap bangunan pengetahuannya sudah terberi dan tergaransi. Rasjidi secara keras mengkritik gagasan Nurcholish Madjid yang menganjurkan sekularisasi tanpa sekularisme, sebuah usulan yang dianggapnya tidak masuk akal, dan gagasan Harun Nasution. Rasjidi bahkan menulis kritik berbentuk buku terhadap Nasution, Koreksi terhadap Dr Harun Nasution. Dalam buku itu, Rasjidi mengkritik upaya Nasution untuk melakukan analisis historis terhadap perkembangan filsafat politik dan aliran teologi dalam Islam sebagai langkah yang akan membingungkan dan merusak keimanan mahasiswa. Bagi Rasjidi, eksperimen politik awal Islam, meski penuh konflik, tetaplah periode emas dan contoh baik yang harus diemulasi, serta berbagai aliran teologis pinggiran dalam Islam, seperti Mu’tazilah dan berbagai kelompok Syiah, tidak memberikan alternatif apa pun bagi ajaran Islam arus utama di Indonesia.
***
Pada bab keempat, Abbas membahas “episode McGill” jilid dua, yang kali ini bertempat di kampus berbeda: Universitas Chicago. Di Chicago, “broker intelektual” dari fusionisme adalah Leonard Binder dan Fazlur Rahman. Berbeda dengan Smith yang merintis fusionisme di IIS, Binder dan Rahman mengembangkan fusionisme dalam konteks yang lebih suportif. Ford Foundation, sebuah lembaga filantropis terkemuka, bersedia memberikan dukungan finansial kepada proyek riset Islam dan perubahan sosial yang dijalankan dua sarjana tersebut. Selanjutnya adalah sejarah. Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Ahmad Syafii Maarif--yang kelak dikenal sebagai “tiga pendekar dari Chicago”—direkrut sebagai mahasiswa doktoral oleh Binder dan Rahman. Nurcholish Madjid, yang awalnya dijuluki “Natsir muda,” menggegerkan dunia pemikiran dan pergerakan Islam Indonesia karena gagasannya tentang sekularisasi dan slogannya “Islam Yes, Partai Islam No,” sedangkan Amien Rais dan Syafii Maarif memiliki reputasi sebagai intelektual-aktivis muda Muhammadiyah terkemuka.
Agenda riset fusionis Binder dan Rahman memiliki dua pertanyaan besar, yaitu bagaimana agama memengaruhi proses modernisasi dan politik modern (Binder) dan sebaliknya bagaimana modernisasi memengaruhi praktik dan lembaga agama (Rahman). Agenda riset fusionis Chicago juga dapat dikatakan lebih reflektif dan sadar dengan pentingnya menjembatani dikotomi perspektif “orang luar” dan “orang dalam,” imperialisme akademik, dan juga kekayaan kultural dan intelektual dari tradisi Islam maupun modernitas Barat. Baik Binder maupun Rahman percaya bahwa fusionisme intelektual dan metodologis akan membantu untuk menemukan dan merumuskan universalitas yang mengandung nilai kebenaran melalui investigasi historis yang ketat—tatanan liberal-demokratik bagi Binder dan nilai-nilai Islam bagi Rahman.
Ketiga pendekar Chicago dari Indonesia menanggapi panggilan fusionis Binder-Rahman dengan cara masing-masing. Madjid membahas Ibnu Taimiyah dalam disertasinya dan menantang pembacaan konservatif atas Ibnu Taimiyah oleh kalangan Islamis dengan berargumen bahwa ijtihad justru dimungkinkan dalam kerangka berpikir Ibnu Taimiyah karena alternatifnya, taklid, justru rawan membuat umat Islam “menyembah” penafsiran manusia yang penuh kekurangan atas ajaran agama. Rais menulis disertasi berdasarkan riset lapangan tentang politik Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir dengan mengkritik program politik IM yang sekadar menonjolkan klaim tentang Islam yang murni tanpa menjelaskan impelementasi riil dari klaim ideologis tersebut. Sementara itu, Maarif yang menggunakan metode Rahman untuk membedakan antara Islam yang normatif dan Islam yang historis menunjukkan bagaimana rumah organisasionalnya, Muhammadiyah, belum konsisten dalam menerapkan prinsip ijtihad dan juga mengkritik gagasan negara Islam.
Akan tetapi, hantu imperialisme akademik dalam proyek fusionisme belum benar-benar terusir, fenomena yang dibahas Abbas di bab kelima. Kenaikan perspektif dan jaringan fusionis dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia juga dibarengi dengan kemunculan kritik atas fusionisme, terutama dari perspektif pasca-modernisme dan pasca-kolonialisme. Naiknya cendekiawan muslim dalam kancah politik dan intelektual nasional di Muhammadiyah dan Paramadina juga dibarengi dengan kritik reflektif atas bias kolonialis dan imperialis dalam kajian Islam yang ditutupi dengan klaim “ilmiah.”
Dalam bab itu, ada dua studi kasus resistensi terhadap bayang-bayang imperialis dari fusionisme. Pertama adalah Amien Rais. Berbeda dengan dua rekan pendekar Chicago lainnya, fusionisme Amien Rais lebih bersifat pragmatis dan utilitarian. Bahkan, Rais menggunakan kritik pascakolonial Edward Said dalam bukunya, Orientalism, terhadap bias-bias orientalis yang dibungkus sebagai klaim akademik dalam kajian Islam di Barat.[1] Akan tetapi, Rais tetap mendorong partisipasi kader dan cendekiawan muslim dalam sistem akademik dan penelitian Barat demi terbentuknya lapisan muslim terdidik yang dapat menjawab berbagai permasalahan masyarakat. Resistensi yang lain didorong oleh DDII melalui majalahnya, Media Dakwah, ketika mereka menggugat analisis R William Liddle, seorang Indonesianis terkemuka, yang memuji kalangan muslim modernis fusionis seperti Nurcholish Madjid dan mengkritik DDII sebagai kelompok yang tertutup secara intelektual, berpikir dalam kerangka konspiratorial, dan memiliki musuh-musuh imajiner. Para editor Media Dakwah menyerang balik Liddle sebagai antek imperalisme dan sekulerisme Barat, khususnya Amerika Serikat, lengkap dengan berbagai karikatur anti-Semitik. Meski vulgar, konyol, dan dangkal, Media Dakwah menyoroti satu isu penting, yaitu timpangnya relasi kuasa antara para sarjana Barat pengkaji Islam (dan para mahasiswa muslim bimbingan mereka) dengan masyarakat muslim dan juga kelompok-kelompok muslim yang dianggap kolot.
***
Pada bab terakhir, bab kesimpulan, Abbas mengidentifikasi tiga pilihan yang bisa diambil oleh para pengkaji Islam dalam merumuskan hubungan mereka dengan tradisi dan masyarakat yang mereka kaji. Pertama adalah menjaga batas kajian Islam akademik/Barat dengan praktik keberagamaan di masyarakat muslim. Pilihan itu problematis karena mengecilkan nilai ilmiah karya-karya cendekiawan muslim, mengasumsikan dikotomi “analisis akademik” dan “praktik keberislaman” sebagai kategorisasi yang stabil dan rawan mereproduksi bias Orientalis. Pilihan kedua adalah dialog kritis lintas tradisi diskursif. Pilihan itu, meski tidak mudah, mengajak para pelajar dan pengkaji Islam untuk meneruskan proyek fusionisme dengan sentuhan sensibilitas pascakolonial. Pilihan itu lebih baik dari pandangan dikotomis dan esensialis perspektif pertama, tetapi tetap menyisakan satu pertanyaan penting: siapa yang berhak diundang dalam dialog lintas tradisi tersebut? Pilihan terakhir adalah tawaran dari intelektual Palestina Wael Hallaq: introspeksi radikal. Dengan kata lain, setiap pengkaji Islam, terutama yang datang dari konteks akademik Barat/modern, perlu menguliti secara mendetail dan menyeluruh apakah kerja akademik yang dilakukannya akan berkontribusi ke subjugasi dan dominasi pengetahuan serta kekerasan intelektual terhadap masyarakat muslim yang mereka teliti? Namun, Hallaq kurang menjelaskan langkah-langkah riil yang harus diambil untuk menyudahi kekerasan intelektual itu.
Abbas berhasil membahas sebuah fragmen penting dari sejarah intelektual Islam di Indonesia secara baik dan cermat dalam buku ini. Dia berhasil menemukan kebaruan empiris dan juga kerangka analitis dengan membahas peran pendidikan Barat dalam membentuk khazanah pemikiran Islam di Indonesia dan ketegangan antara dualisme dan fusionisme. Alur penulisan buku juga mudah diikuti dan penuturannya, setidaknya dalam versi bahasa Inggris, mudah dipahami.
Di saat yang bersamaan, sebagai sebuah buku yang baik, buku ini juga menggelitik saya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan, kritik, dan usulan tambahan. Saya mulai dari satu topik empiris yang tidak terlalu dibahas oleh Abbas: bagaimana cendekiawan muslim dari kubu tradisionalis menanggapi perdebatan dualisme versus fusionisme? Tentu kita bisa memahami bahwa kelompok-kelompok muslim modernis natural memiliki hubungan yang lebih dekat dengan institusi pendidikan modern seperti kampus-kampus Barat. Akan tetapi, sedikit pembahasan tentang bagaimana para cendekiawan muslim tradisionalis Indonesia menanggapi perdebatan tersebut akan membuat buku Abbas menjadi lebih menarik dan kuat.
Kita juga bisa sedikit menggugat fokus studi kasus cendekiawan muslim modernis yang dipilih Abbas. Ada dua cendekiawan Muhammadiyah berpendidikan Barat yang luput dibahas oleh Abbas: Kuntowijoyo dan Moeslim Abdurrahman. Kuntowijoyo meraih gelar doktor bidang sejarah dari Universitas Columbia, aktif sebagai akademisi dan sastrawan, serta mengembangkan gagasan fusionis yang bisa dibilang lebih garang dan kekiri-kirian, yaitu Ilmu Sosial Profetik. Sementara itu, Moeslim Abdurrahman meraih gelar doktoral bidang antropologi dari Universitas Illinois Urbana-Champaign dan menggagas fusionisme yang juga kekiri-kirian bertajuk Islam Transformatif. Fusionisme Kuntowijoyo dan Abdurrahman, menurut saya, memiliki karakter yang berbeda dengan fusionisme McGill atau Chicago.[2]
Yang juga tidak kalah menarik adalah pertemuan dengan fusionisme yang dialami oleh cendekiawan muslim yang tidak menempuh studi di Barat secara langsung, tetapi bertemu dengan literatur-literatur ilmu sosial dan humaniora modern, seperti M Dawam Rahardjo dan Abdurrahman Wahid. Sedikit pembahasan tentang tokoh-tokoh itu juga akan memperkuat argumen Abbas.
Secara metodologis, karya Abbas juga akan lebih kuat bila mengintegrasikan pembacaan yang lebih atentif terhadap faktor-faktor material domestik yang menyebabkan kenaikan fusionisme di Indonesia. Fusionisme tersebut dimungkinkan karena adanya interaksi di antara para cendekiawan muslim Indonesia dengan institusi universitas modern di Tanah Air, Timur Tengah, dan Barat. Dengan kata lain, ada proses-proses material dan struktural yang lebih besar–dan bahkan bisa dibilang melatarbelakangi–di balik pertemuan ideasional antara cendekiawan muslim Indonesia dengan rekan-rekan fusionis mereka di belahan dunia lain. Secara jitu dan detail, Abbas menunjukkan bagaimana pertemuan dan koalisi fusionisme Islam lintas negara dan benua berada di dalam konteks pasca-kolonialisme dan Perang Dingin alias faktor struktural global. Penjelasan itu akan lebih kuat jika Abbas juga membahas mengenai sejumlah faktor material domestik, seperti kenaikan kelas menengah muslim yang dimungkinkan oleh pembangunan kapitalistik Orde Baru dan orientasi intelektual mereka yang cenderung reformis-fusionis.[3]
Kemudian, buku ini juga akan lebih menarik jika Abbas membahas mengenai trayektori perdebatan fusionisme versus dualisme pasca-Reformasi. Dengan kata lain, transmutasi dari perdebatan-perdebatan yang ada sebelumnya serta aktor-aktor yang terlibat. Ada dua kasus transmutasi yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu trayektori Amien Rais dan para intelektual Jaringan Islam Liberal (JIL). Keduanya menunjukkan bagaimana para cendekiawan muslim yang sempat mengalami fase cemerlang dan berkontribusi dalam perdebatan fusionisme-dualisme akhirnya mengalami pengerdilan (bastardization) intelektual dan politik.
Amien Rais, misalnya, berubah dari seseorang dengan reputasi reformis dan fusionis-kritis menjadi seorang politisi dan komentator sektarian. Rekam jejaknya di Muhammadiyah masih berlanjut di periode awal Reformasi melalui partai politik yang didirikannya, Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, kita dapat mengatakan bahwa Amien Rais memiliki reputasi populis. Namun, trayektorinya di kemudian hari mengalami involusi dan bahkan degenerasi. Rais mendekatkan dirinya dengan sejumlah figur populis kanan seperti Prabowo dan para elite Gerakan 212 dan mendirikan Partai Ummat sebagai bagian dari proses hijrahnya dari “modernis Islam yang berubah menjadi konservasionis Islam.”[4] Langkah Amien Rais bisa dibaca sebagai strategi oportunistis dan vulgar, sebuah pembacaan yang saya rasa valid. Di sisi lain, petualangan politiknya juga dapat dibaca sebagai koreksinya terhadap fusionisme Islam kritis dan apresiasinya terhadap aspek-aspek Islamisme, termasuk pembacaan dualis atas pengetahuan.
Transmutasi yang lebih menakjubkan terjadi pada para intelektual JIL. Pada periode awal kemunculannya, JIL banyak disambut oleh kalangan intelektual dan masyarakat sipil Tanah Air sebagai pewaris dari fusionisme Islam Indonesia. Pemikiran mereka di bidang teologi, fikih, dan isu-isu kontemporer, yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang Islam tradisional dan literatur ilmu sosial, humaniora, dan filsafat Barat, dianggap inovatif, bahkan provokatif, dan membuka cakrawala baru tentang Islam di dunia modern. Akan tetapi, pada periode selanjutnya, JIL mengalami kemunduran yang luar biasa. Tentu saja, sebagai gerombolan liberal, para eksponen JIL cenderung abai dengan isu-isu struktural yang dihadapi oleh lapisan-lapisan masyarakat yang paling tertindas dan dieksploitasi serta relasi mereka dengan struktur ekonomi-politik industri pendanaan masyarakat sipil global.[5] Penerimaan mereka terhadap ide-ide pasar bebas dan retorika “anti-fundamentalisme” serta “anti-utopianisme” dalam pengertian sempit juga mengurangi nilai kritik dan reputasi sosial mereka. Lebih parahnya lagi, eksperimen politik mereka dengan berpartisipasi sebagai politisi partai borjuis atau pendukung politisi elitis, seperti Partai Demokrat (PD), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Basuki Tjahaja Purnama, dan Joko Widodo, terbukti mandek atau bahkan gagal, menunjukkan bahwa mereka sekadar sekelompok pecundang politik.
Tentu saja, kedua bahasan tersebut berada di luar fokus Abbas. Bagaimanapun juga, bukunya akan makin lebih menarik dan tentunya provokatif jika sang penulis bisa membahas—dan sedikit mengolok-olok secara elegan dan jenaka—tentang degradasi intelektual dan politik sejumlah cendekiawan muslim Indonesia yang menempuh studi di Barat dan terpapar dengan debat fusionisme versus dualisme.
***
Dari segi metodologi, dua studi kasus di atas juga menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pembacaan yang berbau biografis dan psikoanalisis untuk membaca motivasi personal dan berbagai dorongan bawah sadar yang mendorong aktor-aktor intelektual muslim bergumul dalam debat fusionisme versus dualisme Islam. Adakah, misalnya, struktur insentif yang mendorong para sarjana muslim itu untuk terlibat, berpartisipasi, dan mengamini kerangka perdebatan yang ada? Adakah upaya dari para sarjana dan cendekiawan muslim Indonesia kontemporer untuk keluar dari kerangka debat dan diskusi yang ada tentang ketegangan epistemik antara Islam dan Barat? Apakah “jenjang karier” sebagai intelektual kelas menengah—atau bahkan intelektual mapan, sebagaimana dapat kita lihat dalam keberhasilan sejumlah cendekiawan dan peneliti muslim untuk “banting setir” ke industri lembaga survei dan konsultan politik—terlalu menggoda untuk ditinggalkan dan dilampaui?
Dalam tataran yang lebih reflektif, penelusuran Abbas akhirnya bermuara ke sejumlah pertanyaan besar: mungkinkah perlawanan dilakukan oleh para cendekiawan dan sarjana muslim kritis terhadap hegemoni dan dominasi dunia akademik Barat dan segenap aparatus corak produksi pengetahuannya? Selanjutnya, apakah apropriasi kreatif atas tradisi akademik dan intelektual modern/Barat dimungkinkan? Kemudian, apa sasaran yang hendak dicapai dari “jihad intelektual” berupa apropriasi kreatif dan dekolonisasi tersebut? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang perlu dijawab oleh setiap cendekiawan muslim Indonesia, terutama mereka yang memiliki kerangka analitis kritis dan cita-cita emansipasi sosial, yang menempuh studi di Barat.●
Iqra Anugrah
Catatan akhir:
[1] Lihat, Edward W Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
[2] Beberapa karya utama Kuntowijoyo adalah sebagai berikut: Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991); Menuju Ilmu Sosial Profetik (Bandung: Republika, 1997); Muslim tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental (Bandung: Mizan, 2001); dan Islam Sebagai Ilmu (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). Sementera itu, beberapa karya pokok Moeslim Abdurrahman, antara lain, disertasi doktoralnya, “On Hajj Tourism: In Search of Piety and Identity in the New Order Indonesia” (Department of Anthropology, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000) dan buku-bukunya, Islam Transformatif (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996); Islam sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003), dan Islam yang Memihak (Yogyakarta: LKiS, 2005).
[3] Untuk pembahasan ekstensif mengenai kenaikan kelas menengah di Asia dan Indonesia dekade 1990-an; lihat, Richard Robison dan David SG Goodman (eds.), The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds, and Middle-Class Revolution (London and New York: Routledge, 1996) serta Richard Tanter dan Kenneth Young (eds.), The Politics of Middle Class Indonesia (Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990).
[4] Pengakuan ini dapat dilihat di website Partai Ummat, https://partaiummat.id/id/?page_id=26
[5] Kritik terhadap persoalan ini saya jabarkan dalam artikel saya, “Recent Studies on Indonesian Islam: A Sign of Intellectual Exhaustion,” dalam Indonesia, Vol. 100, 2015, hal. 107-108.